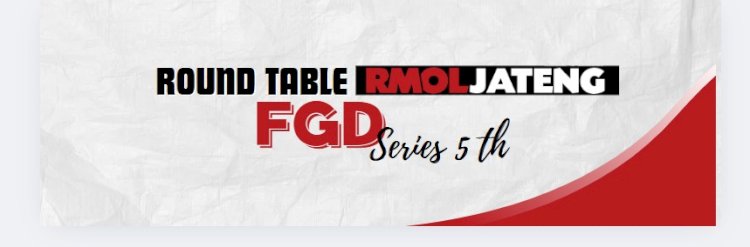Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pasca pandemi COVID-19 terus menunjukkan pemulihan ke arah kondisi normal.
Dilihat menurut lapangan usaha, sektor-sektor penunjang pariwisata menunjukkan pertumbuhan pasca pandemi COVID-19, seperti sektor Akomodasi dan Restoran yang memberikan pertumbuhan tertinggi hingga tahun 2022 sebesar 16,99 persen, demikian pula tahun tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 11,24 persen.
Berdasarkan data dari Badan pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk usia kerja, yakni penduduk di atas 15 tahun pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 29,71 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 334,55 ribu orang atau meningkat 6,86 persen dibandingkan dengan Agustus 2023.
Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja sebanyak 21,91 juta orang, sedangkan sisanya bukan angkatan kerja sebanyak 7,8 juta orang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 20,86 juta orang dan pengangguran sebanyak 1,05 juta orang.
Masih banyaknya pengangguran tersebut dapat dipahami jika kondisi tersebut menyumbang angka kemiskinan. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023 - Maret 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebanyak 13,85 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 101,02 ribu orang.
Secara persentase, kemiskinan di perkotaan turun dari 9,78 persen menjadi 9,71 persen. Demikian juga di perdesaan turun dari 11,87 persen menjadi 11,34 persen. Sebagian besar penduduk di Jawa Tengah bekerja pada lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan sebanyak 5,33 juta orang atau sebesar 25,54 persen;
Desa Inovatif
Dari fenomena pengangguran, kemiskinan, dan belum optimalnya sektor pertanian menyumbang PDRB Provinsi Jawa Tengah, maka kehadiran Desa Inovatif menjadi alternatif untuk mengembangkan ekonomi kreatif.
Kehadiran desa inovatif di panggung perekonomian nasional menjadi satu pemikiran yang menarik untuk dikaji dan ditindaklanjuti karena persoalan-persoalan sebagai berikut. Pertama, arus urbanisasi kini menjadi fenomena nasional bahkan global, dan ini artinya desa-desa bisa juga dikaitkan dengan kelangkaan lapangan kerja.
Kedua, Petani pangan kita saat ini hanya mampu memenuhi 30 % dari kebutuhan keluarganya (lahan 1 ha), padahal jumlah mereka sekitar 72 % dari total petani; Ketiga, jumlah petani gurem yang berlahan sempit makin banyak.
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyebutkan 71 persen tanah di seluruh daratan di Indonesia telah dikuasai korporasi kehutanan. 23 persen tanah dikuasai oleh korporasi perkebunan skala besar, para konglomerat dan sisanya dimiliki masyarakat.
Keempat, konversi lahan dan pewarisan tanah pertanian terus terjadi dengan pesat, akibatnya produktivitas pertanian juga menurunan yang ditandai sumbangannya terhadap PDRB berkurang.
Fakta ini diperparah oleh masuknya petani dalam perangkap pangan (food trap). Dari hulu sampai hilir, pupuk, obat-obatan, bibit tanaman, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran, dst, dikuasai MNCs-MNCs (kapitalisme raksasa).
Dari latar belakang itulah, kehadiran desa inovatif menjadi keniscayaan, yakni desa yang mampu mengarahkan orientasi pembangunan yang bersifat menyeluruh, terkait dengan pengembangan SDM, SDA, lingkungan, sosial, budaya, politik dan kewilayahan. Kesemuanya dapat dicapai dengan jalan mengerahkan segenap potensi masyarakat yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, teknologi dan informasi untuk ditularkan kepada masyarakat pedesaan.
Manajemen Desa Inovatif
Inovasi adalah gagasan, perbuatan, atau sesuatu yang baru dalam konteks sosial tertentu untuk menjawab masalah yang dihadapi. Desa dikatakan inovatif jika desa tersebut sanggup meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi untuk melancarkan perubahan sosial atau pembangunan masyarakat.
Salah satu kunci agar desa menjadi inovatif adalah hadirnya sang pelopor untuk merubah pola pikir masyarakat. Banyak contoh kasus sebuah desa yang memiliki potensi SDA, namun karena nilai-nilai budaya masyarakatnya tidak mendukung, maka potensi itu tinggal potensi saja.
Sebaliknya kasus desa di Cepogo Boyolali yang tidak memiliki potensi alam tambang tembaga misalnya, namun sanggup merubah wajah desa menjadi sentra kerajinan tembaga. Demikian pula desa Tahunan dan Troso di Jepara. Mereka mampu mengembangkan kerajinan ukir dan tenun yang mendunia.
Contoh lain desa inovatif adalah Desa Ponggok di Kabupaten Klaten yang mengembangkan umbul atau mata air menjadi obyek berfoto selfi-ria bagi para remaja.
Siapapun bisa berfoto di dalam air dengan menggunakan media seperti becak, sepeda motor, TV, dsb.
Efek sampingnya adalah menggeliatnya perekonomian masyarakat ketika para wisatawan datang berbondong-bondong, yakni hidupnya jasa kuliner, jasa parkir, jasa persewaan alat menyelam, pasar rakyat, penginapan, souvenir, transportasi dan sebagainya. Semuanya dikelola Bumdes dan menghasilkan PAD-Desa yang luar biasa.
Ada juga Desa Menari di Kabupaten Semarang. Kehadiran sang pelopor yang tahu hobby masyarakat di desa tersebut juga menjadi menjadi kunci penting. Mereka dikoordinir untuk menyajikan tarian-tarian tradisional yang massal, sehingga menjadi daya tarik tersendiri.
Semula sebelum pertunjukkan, saya berniat akan member sekadar “saweran” beberapa ribu rupiah saja. Namun ketika mereka keluar dengan puluhan penari yang serius, baik kostum maupun tariannya, pikiran itu berubah 180 derajad.
Bagi saya, saweran 50 ribu atau 100 ribu sangat pantas. Mereka berhasil mencuri hati para wisatawan, justru dari niat untuk mengekploitasi pemasukan, buktinya tidak ada tiket masuk dan permintaan bayaran.
Justru karena kesederhanaan yang ditunjang keseriusan, wisatawan menjadi tidak pelit untuk member sumbangan. Efek samping dari desa menari tersebut adalah pasar rakyat sebagaimana dialami desa Ponggok di atas. Kesemuanya memajukan kesejahteraan masyarakat desa.
Contoh lain desa inovatif adalah Desa Kaliabu Kabupaten Magelang. Di desa ini ada kelompok pembuat desain logo tingkat dunia yang diberi nama “Rewo-Rewo” (dalam Bhs Jawa tafsir saya pribadi, rewo-rewo artinya orang yang berpakaian sekadarnya dengan baju yang tidak teratur bergelantungan).
Semula ada satu pelopor yang berhasil memenangkan lomba desain logo perusahaan internasional di luar negeri, dan ia mendapat hadiah jutaan rupiah. Kejadian ini berulang dan akhirnya menarik minat puluhan pemuda yang semula menganggur.
Pemuda desa tersebut walaupun tidak memiliki dasar ilmu IT, bahkan berpendidikan rendah, namun berkat pelatihan dari sang pelopor, kini berhasil menghasilkan nafkah, karena ikut memenangkan lomba-lomba desain logo.
Kunci dari desa inovatif adalah hadirnya sang pelopor yang memiliki visi jauh ke depan, lengkap dengan aksi-aksinya yang nyata. Dari berbagai sumber, untuk meyakinkan masyarakat Desa Cepogo, Desa Ponggok, Desa Menari, Desa Kaliabu, dsb, sangatlah sulit.
Sang pelopor tidak sim salabim, namun harus paham kunci utama perubahan sosial masyarakat, yakni tahu hobby alias kesenangan mayoritas masyarakat, dan tentu dilengkapi data tentang desa yang komplit.
Selanjutnya, mengoptimalkan kualitas SDM berikut perangkat desa dan pendamping desa, seperti : penggunaan data kependudukan desa, penguasaan manajemen perencanaan, dan pemahaman serta analisis data, dst.
Dengan memahami struktur dan dinamika penduduk akan dapat direncanakan hendak kemana desa akan dikembangkan.
Dalam proses penyebaran inovasi adalah (1) anggota sistem sosial yang akan menerima inovasi (2) agen pembaru yang membawa ide (3) tokoh masyarakat yang yang menjadi sumber keputusan pengadopsiaan inovasi (4) saluran atau sistem komuniasi yang digunakan dalam proses sosialisasi.
Keberhasilan pembangunan di perdesaan tidak hanya tergantung pada ukuran ekonomis seperti pertumbuhan (growth), namun juga seberapajauh keterlibatan seluruh masyarakat dalam pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan.
Hanya pelopor yang memiliki ketelatenan, kesabaran, dan kerja keras yang sanggup merubahnya. Dari titik inilah peranserta birokarsi di atasnya sangat penting, demikian juga dunia usaha dan dunia industri. 
*) SARATRI WILONOYUDHO. Profesor Ilmu Kependudukan, Ketua Koalisi Kependudukan dan Anggota Dewan Riset Daerah Jateng
- Wali Kota Tegal : Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan Harus Jadi Super Prioritas
- Lindungi Situs Kuno, Banjarnegara dan Kemenkumham Bahas Raperda Cagar Budaya
- Divonis 15 Tahun Atas Kasus Pencabulan Anak, Kuasa Hukum R Berencana Banding