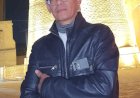- Pemerintah Perlu Waspadai Kebijakan Tarif Impor Trump
- Apakah Ormas Berhak Menjadi Negara Di Dalam Negara?
- Membawa Agama Yang Ekologis Dan Penuh Kasih
Baca Juga
Masuk ke rakyat bukan hanya perkara mengenal nama atau memahami situasi di lokasi pendampingan. Pintu masuk atau entry point, menjadi elemen fundamental dalam membangun relasi awal dengan rakyat. Namun, apakah cukup berhenti di pintu? Pertanyaan ini menguak ironi dalam praktik yang dilakukan organisasi non-pemerintah (NGO) yang seringkali terlalu sibuk dengan program hingga lupa menukik ke akar persoalan.
Tulisan ini bertujuan menelaah kritik dan peluang perbaikan dalam pendekatan NGO di Indonesia, yang seringkali terjebak dalam perangkap apa yang saya sebut sebagai "aktivis program" tanpa orientasi perubahan sosial yang sejati.
Menelisik Titik Masuk: Dari Alat ke Tujuan
Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang (2004) menekankan bahwa pintu masuk hanyalah sebuah sarana untuk membangun hubungan awal, bukanlah tujuan akhir dari proses pengorganisasian. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berkata lain. Banyak pengorganisir memulai program mereka dengan kegiatan-kegiatan spesifik, seperti sosialisasi atau pelatihan. Meskipun kegiatan ini memiliki nilai penting, sayangnya sering kali hanya berhenti pada tataran aktivitas tanpa benar-benar menyentuh permasalahan struktural yang dihadapi oleh komunitas.
Fenomena ini menciptakan metafora yang menohok: "Sudah berada di depan pintu, bahkan sudah punya kunci dan sudah membuka pintunya, tapi tidak pernah masuk ke dalam rumah." Para pengorganisir sibuk dengan indikator keberhasilan program, tetapi gagal mengangkat kesadaran kritis rakyat untuk menghadapi akar permasalahan. Apakah ini karena kurangnya pemahaman, atau ada faktor lain yang lebih sistemik?
Kritik yang lebih dalam mengarah pada apa yang disebut sebagai tesis westernisasi. Kenny dkk (2010) menunjukkan bahwa ketergantungan NGO pada pendanaan internasional, khususnya dari negara-negara Barat, memengaruhi cara mereka bekerja. Pendekatan berbasis statistik, laporan donor, dan tata kelola organisasi yang mengutamakan efisiensi sering kali mengerdilkan fokus pada isu-isu struktural.
Pendanaan ini menciptakan tekanan bagi NGO untuk menyesuaikan diri dengan logika donor, mengorbankan sensitivitas lokal dan kebutuhan rakyat. Alih-alih mengorganisasi rakyat untuk mengatasi persoalan mendasar, NGO justru terjebak dalam apa yang disebut Arundhati Roy sebagai "NGO-isasi." Fenomena ini menjadikan NGO sekadar pelaksana program-program "sopan" yang dirancang untuk memenuhi standar donor, bukan agenda transformasi sosial.
Aktivis Program: Sebuah Sindiran Tajam
Ali Fikri Hamdhani (2024) dalam artikelnya menggambarkan jebakan aktivis program sebagai kesibukan yang melenakan. Program-program yang dirancang dengan struktur rapi sering kali gagal menjawab persoalan mendasar rakyat. Aktivis program ini memprioritaskan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas di mata donor, tetapi abai terhadap kesadaran politik rakyat sebagai subjek utama perubahan sosial.
Jika pendekatan NGO terus terjebak dalam logika ini, maka perubahan struktural menjadi mustahil. Harapan pada "political will" dari elit penguasa hanyalah angan kosong. Sebaliknya, hanya rakyat yang terorganisasi dengan kesadaran politik tinggi yang mampu menciptakan perubahan nyata. Maka, fokus NGO seharusnya tidak hanya pada pelaksanaan program, tetapi juga pada kerja-kerja penyadaran yang berorientasi jangka panjang.
Kerja NGO juga tidak dapat hanya sebatas pelengkap atau charity semata, yang sekadar menyalurkan bantuan tanpa menyentuh akar persoalan. Peran kritis mereka dalam mendorong transformasi sosial menjadi semakin mendesak, terutama di tengah menjamurnya program-program yang secara tidak langsung melemahkan daya kritis rakyat terhadap isu-isu struktural. Salah satu contohnya adalah Program Negara bertajuk Makan Bergizi Gratis.
Meski pun program ini tampak mulia di permukaan, ia gagal menyentuh inti permasalahan struktural terkait sistem pangan, seperti ketimpangan distribusi, monopoli rantai pasok, hingga akses rakyat marginal terhadap pangan yang layak. Program semacam ini tidak hanya gagal mengatasi akar masalah, tetapi juga berisiko melanggengkan ketergantungan rakyat pada bantuan sementara tanpa memberikan solusi yang berkelanjutan.
Fokus NGO yang terlalu terpaku pada keberlanjutan proyek pembangunan dan pengajuan proposal baru sering kali mengabaikan pentingnya pemberkuasaan rakyat lokal secara mendalam. Ketergantungan pada proyek bantuan menciptakan hubungan yang tidak setara, di mana komunitas hanya menjadi penerima pasif tanpa akses pada proses pengambilan keputusan. Akibatnya, masalah struktural yang menjadi akar persoalan tetap tidak teratasi, sementara rakyat kehilangan kesempatan untuk berkembang sebagai aktor transformasi sosial yang mandiri dan berdaya.
Model kerja yang berorientasi pada charity ini juga mengabaikan potensi transformasi sosial yang seharusnya menjadi inti dari peran NGO. Sebaliknya, pendekatan yang berfokus pada pemberkuasaan komunitas lokal dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, memperkuat solidaritas antarwarga, dan mendorong keterlibatan dalam advokasi kebijakan dapat menciptakan perubahan yang lebih mendasar. Namun, ini membutuhkan keberanian NGO untuk melawan arus pendekatan yang terlalu birokratis dan sering kali dikendalikan oleh logika donor yang mengutamakan hasil jangka pendek.
Pendekatan yang terlalu birokratis dan berorientasi pada hasil jangka pendek ini pada akhirnya melemahkan akar rumput. Alih-alih memperkuat keberlanjutan komunitas lokal, NGO sering kali menciptakan model ketergantungan yang sulit dihilangkan. Dengan semakin intensifnya tekanan politik terhadap ruang sipil, model ini menjadi semakin tidak relevan. Ada kebutuhan mendesak bagi NGO untuk merefleksikan kembali peran mereka dalam rakyat dan mengarahkan ulang orientasi mereka menuju transformasi sosial yang lebih substansial.
Di tengah tantangan ini, NGO juga perlu merefleksikan kembali pendekatan mereka, memastikan bahwa program-program yang mereka jalankan tidak hanya memberikan manfaat sementara, tetapi juga memberkuasakan rakyat untuk memahami dan mengatasi permasalahan struktural yang melingkupi kehidupan mereka. Dengan demikian, NGO dapat menjalankan peran mereka sebagai katalisator perubahan yang berorientasi pada keadilan sosial dan transformasi yang berkelanjutan, alih-alih sekadar pelaksana proyek-proyek yang dangkal secara politis.
Memaknai Kembali Posisi NGO
Mengatasi jebakan ini memerlukan refleksi mendalam oleh NGO terhadap peran dan pendekatan mereka. Pertama, NGO harus menyadari bahwa mereka bukanlah sekadar pelaksana program, melainkan fasilitator perubahan.
Kesadaran ini harus tercermin dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program, memastikan bahwa pintu masuk melalui program dan kegiatan hanyalah langkah awal menuju transformasi.
Transformasi sosial juga hanya dapat terjadi jika NGO mampu mengadopsi pendekatan yang lebih politis. Artinya, mereka harus berani memperjuangkan hak-hak sipil, membangun aliansi lintas sektor, dan terlibat dalam wacana publik.
Dalam konteks ini, peran NGO bukan lagi sekadar penyedia layanan, tetapi sebagai katalisator perubahan yang mengupayakan keadilan sosial secara menyeluruh. Transformasi sosial juga hanya dapat dicapai jika NGO mampu melepaskan pendekatan business-as-usual mereka. Pergeseran ini membutuhkan waktu, upaya kolektif, dan keberanian untuk mengubah cara kerja yang telah lama mengakar.
Kedua, pendekatan yang terlalu berfokus pada rekomendasi kebijakan atau advokasi jalur legal perlu ditinjau ulang. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar tidak lahir dari dokumen kebijakan, melainkan dari gerakan rakyat yang terorganisir. Oleh karena itu, kerja-kerja penyadaran harus menjadi prioritas utama.
Ketiga, penting bagi NGO untuk membangun model kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Ketergantungan pada pendanaan internasional dapat diminimalkan dengan memberdayakan sumber daya lokal. Model ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan, tetapi juga memastikan bahwa program-program yang dijalankan lebih relevan dengan kebutuhan rakyat.
Pada akhirnya kerja mengorganisasi rakyat bukanlah tugas mudah. Dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan kenyamanan aktivis program dan melangkah ke wilayah yang lebih menantang: menyadarkan rakyat akan hak-hak mereka, membangun solidaritas, dan melawan struktur yang menindas. Dalam konteks ini, NGO harus menjadi katalisator, bukan sekadar pelaksana.
Transformasi ini tidak bisa dicapai dalam semalam.
Namun, dengan refleksi mendalam dan keberanian untuk berubah, NGO dapat kembali ke jalur yang benar. Pintu masuk hanyalah awal; pekerjaan besar menanti di dalam rumah. Jangan biarkan pintu yang sudah terbuka menjadi penghalang untuk melangkah lebih jauh. 
Martin Dennise Silaban, Penulis dan Peneliti di SHEEP Indonesia Institute & Mahasiswa Magister Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, UGM. Berbagai tulisannya sudah dimuat di media nasional maupun lokal seperti The Jakarta Post, Kompas.id, Tempo, Mongabay, Solopos, Lampung post, SuaraMerdeka, GreenNetwork Asia, Tropis.id, Mudabicara.id, rmol.id, Kedaulatan Rakyat, dan Floresa.co.
Referensi
Hamdhani, A. F. (2024). Mengapa NGO dan rakyat sipil selalu gagal? Transisi. Diakses dari https://transisi.org/mengapa-ngo-dan-rakyat-sipil-selalu-gagal/
Kenny, S., Fanany, I., & Rahayu, S. (2010). Community development in Indonesia: Westernization or doing it their way. Community Development Journal.
Tan, J. H., & Topatimasang, R. (2004). Mengorganisir rakyat: Refleksi pengalaman pengorganisasian rakyat di Asia Tenggara. Yogyakarta: SEAPCP, INSIST Press.
- NGOPI Berhasil Kuak Rahasia Kecantikan Bersama Dr. Ratih Nuryanti
- Tim Dinparta Dan Satpol PP Serbu Pujasera Demak
- Pedagang Rod As Kadilangu Serbu Jepara Dan Berkolaborasi Emas Dengan Dinparta Demak