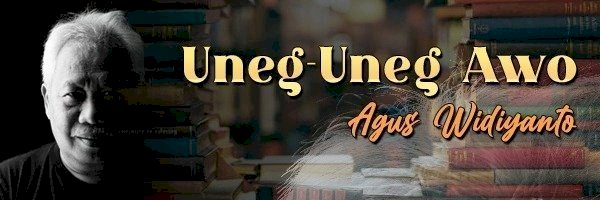Ada seorang dokter bedah saraf yang dalam kanal youtube terlihat cukup bersemangat menceritakan bagaimana Jepang dan negara-negara Skandinavia (Nordik) bisa mendapatkan skor tinggi dalam indek kebahagiaan (Index of Happiness).
Ada seorang dokter bedah saraf yang dalam kanal youtube terlihat cukup bersemangat menceritakan bagaimana Jepang dan negara-negara Skandinavia (Nordik) bisa mendapatkan skor tinggi dalam indek kebahagiaan (Index of Happiness).
- Menanti Perang Ide Andika Perkasa Vs Ahmad Lutfi Di Pilgub Jateng 2024
- Ruwetnya Jagat Permediaan Dan (Masih) Diamnya Pemerintah
- Lengser Keprabon Tetep Kuwasa, Mungkinkah?
Baca Juga
Nama dokter itu Ryu Hasan; lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang melanjutkan pendidikan spesialisas bedah saraf di Sydney Australia kemudian mendalami neurosains di Tokyo Jepang.
Ryu kerap menceritakan bagaimana bangsa Jepang bangkit setelah terpuruk akibat kalah dalam Perang Dunia II, dengan melatih anak-anak sejak dini bagaimana agar terbiasa antre; dibangun empatinya dengan memberi pemahaman bahwa orang yang kehilangan barang itu sedih sehingga jangan mengambil dan memiliki barang milik orang lain.
Meski Jepang ada di peringkat ke-51 dalam indeks kebahagiaan tahun 2024, Ryu mencontohkan Jepang. Maklumlah, dia sepuluh tahun lebih berpraktek di negeri matahari terbit.
Sosok yang terang-terangan mengaku autis, dan sering distigma atheis karena pernyataan-pernyataannya, upayanya patut diapresiasi. Dengan caranya yang unik, slengekan, dan banyak menyisipkan humor ini sejatinya dia sedang mendorong kita untuk mengedepankan rasionalitas, akal sehat, dalam mewujudkan kehidupan bersama yang lebih baik.
Dalam kehidupan keseharian, kita sering menemukan indikasi orang yang senang melihat orang lain susah. Ungkapan seperti “Kapokmu kapan” atau berseru “Syukur” melihat orang yang mengalami kesialan, bukan hal yang asing di lingkungan kita. Perilaku senang melihat orang lain susah bukan hanya terjadi di sini, di belahan negeri lain juga ada.
Fenomena rasa senang, gembira, atau puas yang muncul setelah melihat atau mendengar kabar seseorang yang sedang mengalami kesulitan, kegagalan atau kehinaan yang dalam percakapan keseharian kita dinarasikan “senang melihat orang lain susah” dikenal sebagai "Schadenfreude", kata dalam bahasa Jerman yang berarti perasaan bahagia atau senang ketika melihat orang lain mengalami kesulitan atau kegagalan. Istilah "Schadenfreude" sudah ada, dan tertulis di Jerman sejak tahun 1740-an.
Masyarakat Britania menyebut hal serupa dengan "epicharikaky” sebagaimana dicatat Joseph Nicol Scott dalam “A New Universal Etymological English Dictionary yang terbit tahun 1755. “Epicharikaky” dimaknai sebagai “a joy for the misfortune of others”. Istilah “epicharikaky" atau biasa ditulis dengan “epicaricacy” merupakan kata serapan dari bahasa Yunani epichairekakia.
Jika acuan sikap kita adalah kehidupan yang normal, wajar, dan sehat; sikap yang senang melihat orang lain susah tentunya harus ditolak. Setidaknya, masyarakat harus memegang kesepakatan bahwa sikap “Schadenfreude” adalah hal negatif yang mengganggu kehidupan bersama. Kenapa? Jawabannya sederhana saja: Orang yang bersikap “Schadenfreude” pun tidak mau -minimal tidak suka- kalau dia ditimpa kesialan orang lain memperlihatkan perasaan senang.
Sebaliknya, ada sikap terlalu baik seharusnya dikendalikan agar tak menyulitkan diri pada akhirnya. Kita sering melihat orang yang sikap dan perilaku hidupnya sangat baik, cenderung mulia sampai-sampai mau mengorbankan diri demi orang lain. Secara esensial, bersikap baik kepada orang lain, dan membuat orang-orang di sekitar senang, sebenarnya tidak masalah. Akan tetapi jika selalu ingin menyenangkan orang lain dalam segala keadaan, bahkan berlebihan, itu indikasi seseorang punya kecenderungan menjadi “people pleaser”.
Berbuat dan bersikap baik, memberikan pertolongan adalah hal mulia. Tapi kalau itu dilakukan karena dorongan keinginan menyenangkan orang lain dan dilakukan melampaui kewajaran, bahkan sampai dengan cara yang berlebihan, itu adalah masalah. Orang yang memiliki sifat begitu, pasti sering dimanfaatkan orang lain, bahkan untuk kepentingan yang menyimpang.
Fenomena itu disebut “people pleaser” yang berarti seseorang yang merasakan dorongan kuat untuk menyenangkan orang lain, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Mereka sulit mengatakan “tidak” pada permintaan orang lain. Dalam keadaan tertentu, “people pleaser” bisa mengubah kepribadian mereka di sekitar orang lain.
Orang yang masuk kategori “people pleaser” selain kesulitan untuk mengatakan tidak pada permintaan orang lain, juga memiliki komitmen yang terlalu besar terhadap satu kegiatan Dimana dia terlibat di dalamnya. Mereka juga melakukan pekerjaan ekstra, padahal mereka sendiri memiliki banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan.
Cirir-ciri lain “people pleser” adalah menghindari berselisih paham dengan orang lain, mudah sepakat dengan pendapat orang lain, enggan membela kepentingannya sendiri dan gampang meminta maaf meskipun apa yang terjadi bukan kesalahannya.
Fenomena "Schadenfreude", dan “People pleaser” bukan pelanggaran hukum. Secara etis, juga tidak ada kesepakatan yang tegas untuk melarangnya. Kedua fenomena tersebut juga bukan penyakit. Namun kedua fenomena bisa mengganggu kenyamanan dalam kehidupan bersama. Kehidupan bersama yang dimaksud bukan hanya masyarakat sebagai kesatuan, tapi keluarga sebagai sebuah kesatuan terkecil dalam masyarakat.
Tujuan membangun kehidupan bersama yang utama adalah terwujudnya kebahagiaan kolektif dan invidual tanpa terkecuali. Mungkin ini adalah goal yang ingin diraih Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo sehingga status BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) ditingkatkan menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sebagai pilar dasar masyarakat, keluarga perlu terus dibangun dan didorong agar rangkaian momentum yang dihadapi bangsa dan negara bisa dilewati dengan baik.
Kecenderungan terjadinya "Schadenfreude" dan “People pleaser“ bisa menjadi batu sandungan tujuan mewujudkan keluarga dan masyarakat yang bahagia, sehat dan sejahtera. Keduanya bukan fenomena baru, dan tidak ada tips dan trik untuk menyudahinya dengan mudah dan cepat. Belajar dari negara yang telah mencapai indeks kebahagiaan tinggi, cara mereka mengatasi dua kecendrungan itu adalah dengan mendidik, melatih dan membiasakan masyarakatnya sejak dini untuk menghindari tumbuhnya sikap tersebut.
Soal kita mau memilih apa yang perlu dilakukan, tentunya dikembalikan pada kita semua. “Mau dibawa kemana bangsa kita, tergantung pada kesepakatan kita mau kemana”. 
- KPK: Kabotan Jeneng atau Kabotan Sungu?
- Menyoal Penamaan Polresta Di Wilayah Kabupaten
- Ruwetnya Jagat Permediaan Dan (Masih) Diamnya Pemerintah