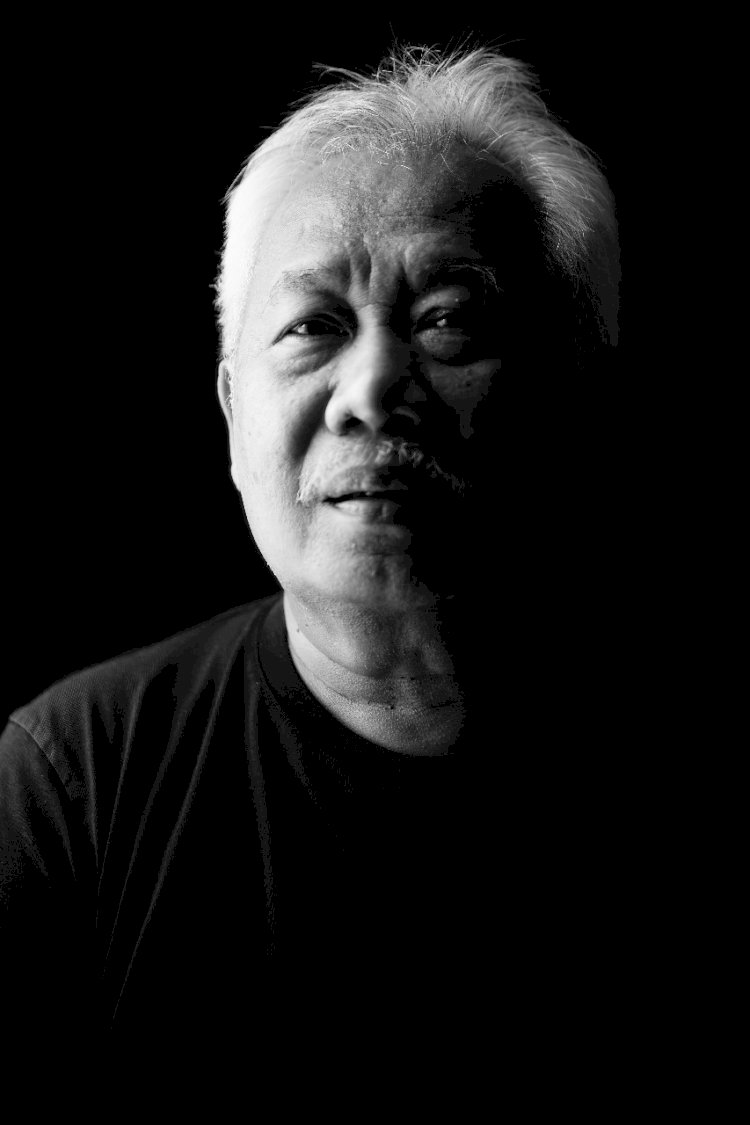Banyak orang yang merasa kecewa, marah, sebel, gemes, nglokro, anyel, apatis melihat kegagalan proyek food estate, pengembangan usaha tani skala luas yang diinisiasi pemerintah.
Banyak orang yang merasa kecewa, marah, sebel, gemes, nglokro, anyel, apatis melihat kegagalan proyek food estate, pengembangan usaha tani skala luas yang diinisiasi pemerintah.
Kegiatan yang berambisi memperkuat ketahanan pangan nasional, dan masuk dalam RPJMN tahun 2020-2024 sekaligus menjadi proyek strategis nasional yang dilaksanakan di 12 lokasi, menjadi bahan olok-olok para kritikus.
Isu kegagalan food estate (lumbung pangan) mencoreng wajah pemerintahan Jokowi. Dan menohok Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang dalam posisinya sebagai Menteri Pertahanan juga terlibat langsung di Kalimantan Tengah.
Sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, selain Kementerian Pertanian yang menjadi leading sector, Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR juga punya peran di sini.
Food estate menurut Badan Litbang Pertanian (Buku Pintar Food Estate 2011) adalah istilah populer dari kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas (di atas 25 hektar) yang dilakukan dengan konsep pertanian yang industrial berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, serta organisasi dan manajemen modern.
Tujuan program food estate adalah mewujudkan ketahanan pangan. Supaya Indonesia bisa mencukupi sendiri kebutuhan pangan masyarakat, tidak selalu tergantung pada impor.
Begitu strategisnya program itu, wajar kalau pelaksanaannya tersebar di beberapa wilayah seperti Sumatra Utara (Sumut), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Tengah (Kalteng), NTT, Papua, dan Papua Selatan. Beberapa tanaman pangan strategis yang dikembangkan terdiri dari bawang merah, bawang putih, singkong, jagung, padi, kacang tanah, kacang hijau, buah mangga, jeruk nipis serta ada Kawasan yang diintegrasikan dengan ternak sapi dan domba. Goalnya, tersedianya pangan dan gizi yang cukup secara merata dan terjangkau bagi masyarakat.
Pertanyaannya, kenapa harus dilakukan secara masif, tersentral dan harus dilakukan dalam areal yang luas? Bukankah sejak awal sudah dipahami bahwa kontribusi sektor pertanian kita berasal dari para petani dengan lahan yang terbatas dengan teknologi usaha tani yang sederhana?
Selama ini konsepsi ketahanan pangan yang sering diidentikan dengan swaswembada pangan seperti meracuni pikiran kita semua. Kecukupan pangan dihitung dalam skala makro, yang celakanya sering tak ditopang dengan kedisiplinan, penghimpunan data-data kecil di lapangan banyak yang diabaikan, atau setidaknya hanya dicatat berdasarkan kebiasaan.
Konsepsi indeks ketahanan pangan dan gizi (IKPG) yang dipakai terasa begitu rumit dan akademik, sehingga tidak mudah dikomunikasikan ke publik. Dalam bahasa masyarakat Jawa, IKPG terlalu ndakik-ndakik, tinggi di awan, bak menara gading penghias kebijakan pangan pemerintah.
Yang harus dipahami, program lumbung pangan nasional ini didanai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebesar Rp1.5 triliun. Memanfaatkan tanah negara, dan tanah yang dikelolakan masyarakat melalui program reforma agraria yang mendistribusikan 3.9 juta hektare (dari 1.3 juta hektare bekas HGU, tanah terlantar, dan 2.6 juta hektare dari pelepasan kawasan hutan).
Ada perdebatan tentang food estate, program yang sebenarnya sudah dirintis sejak era Presiden Soeharto berkuasa. Perdebatan yang sengit adalah anggapan proyek ini gagal, merusak lingkungan, hanya menguntungkan kroni, mengabaikan peta agroklimat dan kritik sejenis itu.
Pemikir moderat menyebut, food estate bukan gagal tapi perlu waktu karena tanah yang dipakai butuh proses untuk bisa produktif. Kaum moderat juga menyebut kurang tersedianya tenaga pertanian dengan kecakapan yang memadai menjadi kendala tersendiri.
Pemerintah menegaskan food estate bukan pekerjaan mudah, namun penting dan strategis karena ketersediaan pangan adalah satu pilar ketahanan nasional yang penting. Sama dengan pendapat pengamat moderat, penguasa dan pendukungnya berpendapat perlu waktu setidaknya enam kali masa panen untuk memvonis berhasil atau gagalnya proyek ini. Sebab penanaman di lahan baru untuk tanaman semusim, perlu uji dan penyesuaian-penyesuaian.
Memakai kata kunci ketahanan pangan, sebaiknya kita fanatik berpangku pada angka makro yang mengukur angka swasembada begitu rumit dan teoritis. Mungkin perlu dilakukan penyederhanaan kosep komunikasi ketahanan pangan yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Misalnya dengan menyebutnya sebagai Swasedia Pangan.
Yang dimaksud Swasedia Pangan adalah kemampuan keluarga dan kelompok menyediakan sendiri kebutuhan pangannya memanfaatkan tanah dan ruang yang dimiliki atau setidaknya dalam pengelolaannya.
Contoh sederhana, karena cabai adalah kebutuhan semua keluarga yang sama pentingnya dengan beras, pemerintah harus mendorong masyarakat menyediakan sendiri kebutuhan cabainya memakai ruang atau tanah yang dikelolanya. Kalau ada lahan milik pemerintah, bisa dipakai sebagai lahan kelompok seperti RT (Rukun Tetangga) dan Rukun Warga (RW).
Jenis tanaman pangan bisa ditambah dengan terong, bayam, selada, kangkung, kacang panjang dan lainnya. Untuk penopang protein bisa dengan membudidayakan lele, gurami, dan jenis ikan air tawar yang mudah pemeliharaannya. Yang lahannya cukup, bisa memelihara ayam untuk dimanfaatkan telur dan dagingnya. Kalau hasilnya lebih dari kebutuhan, bisa dibarter dengan bahan pangan lain dari sesama warga; atau dijual ke pasar.
Ingat, ada 27 juta petani perorangan di Indonesia. Jika dia kepala keluarga yang memiliki 4 orang anggota setidaknya sudah seratus juta lebih orang bisa masuk Program Swasedia Pangan. Jika itu ditambah aksi Smart Farming seperti yang dilakukan Kota Semarang dan dirintis di sebagian wilayah Jakarta, juga di Yogyakarta yang diinisiasi oleh Fakultas Pertanian UGM, program swasedia pangan menjadi signifikan.
Aksi swasedia pangan secara mikro, yang kecil-kecilan, jika dihimpun datanya dengan baik akan muncul data agregat yang mengejutkan. Buatlah aplikasi publik untuk partisipasi dalam program ini. Jangan lupa, berilah insentif. Lumbung pangan yang relevan adalah ketersediaan pangan yang ada di tangan warga, bukan angka-angka makro yang memusingkan.
Untuk mewujudkannya, diperlukan inovasi kelembagaan (Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan) serta riset-riset yang relevan. Saatnya Fakultas Pertanian, Peternakan, Perkikanan dan para sarjana membuat inovasi yang relevan. 
Tulisan merupakan opini pribadi, tidak merepresentasikan atau mewakili organisasi/institusi/lembaga RMOLJawaTengah.
- Dindagkop UKM Rembang Mulai Lakukan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Merah Putih
- MTI Serukan Pentingnya Masterplan Untuk Integrasi Dan Keberlanjutan
- Terpeleset Masuk Sumur, Lansia Di Mrebet Ditemukan Tak Bernyawa