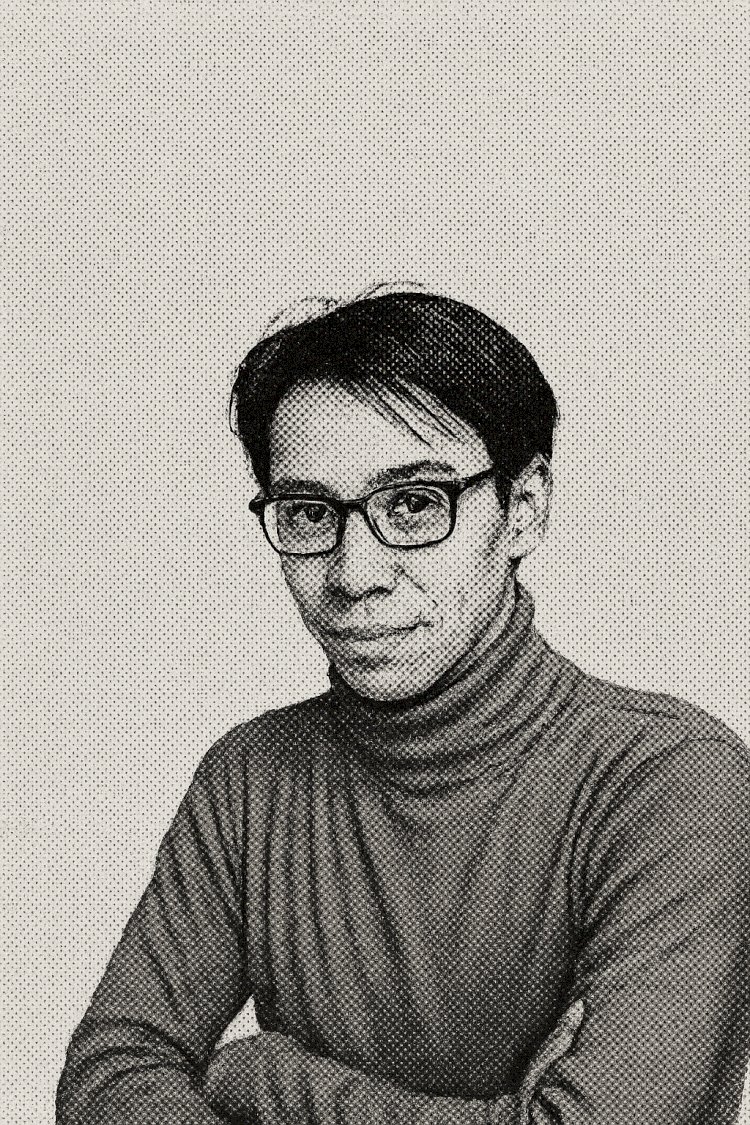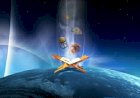- Menteri Dudy Purwagandhi Terbukalah Menerima Masukan, Jangan Alergi Dengan Pemerhati Dan Penggiat Transportasi!
- Menjaga Komunitas Badui Di Tengah Gurun Sinai
- Rais Abin: Jenderal Yang Mengawal Damai Dari Padang Sinai
Baca Juga
Pendidikan, dalam tatanan peradaban manusia, bukan hanya sebatas aktivitas transfer pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia adalah praksis peradaban, denyut nadi kemanusiaan, serta fondasi etik dari sistem sosial yang sehat. Namun, dalam arus modernitas dan industrialisasi kebijakan, pendidikan direduksi menjadi alat reproduksi tenaga kerja dan komodifikasi nilai-nilai kognitif. Supremasi pendidikan — sebagai kekuatan moral dan intelektual pembentuk karakter bangsa — perlahan-lahan dikaburkan oleh obsesi terhadap hasil, bukan proses. Dalam konteks inilah, opini ini berupaya mengangkat kembali supremasi pendidikan sebagai praksis mendidik, bukan sekadar mengajar.
Kegagalan Sistemik: Pendidikan Yang Menyimpang Dari Tujuan Dasarnya
Dalam sistem pendidikan modern, terutama di negara berkembang, terjadi sebuah ironi besar: institusi yang semestinya membebaskan justru menjadi alat penjinakan. Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed menyebut sistem seperti ini sebagai banking education — di mana guru seolah-olah menjadi pemilik pengetahuan, dan murid hanyalah celengan kosong yang diisi lalu diuji. Tidak ada dialog. Tidak ada refleksi. Hanya penghafalan, pengulangan, dan ketundukan pada standar.
Tujuan utama pendidikan semestinya adalah memanusiakan manusia. Namun dalam sistem birokratis saat ini, orientasi pendidikan lebih tertuju pada pencapaian angka-angka statistik: nilai ujian, akreditasi, ranking PISA, dan angka partisipasi kasar. Semua itu penting, tetapi bukan tujuan utama. Ketika pendidikan diukur hanya dari output, kita menciptakan generasi teknokrat, bukan pemikir. Kita membangun manusia industri, bukan manusia reflektif.
Lihatlah bagaimana kurikulum sering kali berubah mengikuti siklus kekuasaan, bukan kebutuhan intelektual. Kurikulum menjadi arena politis — bukan instrumen pembebasan. Guru dipaksa menjadi pengikut silabus, bukan fasilitator pemikiran. Murid dibentuk menjadi pekerja, bukan warga negara. Maka tidak mengherankan jika krisis integritas, empati, dan nalar menjadi problem laten generasi pasca-milenial. Pendidikan kehilangan supremasinya sebagai ruang mendidik, ia hanya menjadi ruang administratif dan pelatihan kerja.
Paradoks Pendidikan Tinggi, Menara Gading Atau Menara Dagang?
Pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi pusat inovasi dan refleksi kritis, kini menjelma sebagai lembaga produksi gelar. Universitas berlomba-lomba membuka program studi sesuai pasar kerja, bukan sesuai tantangan zaman. Ilmu filsafat, antropologi, sastra, dan pemikiran kritis lainnya perlahan tersisih — dianggap tidak produktif secara ekonomi. Inilah bentuk paling nyata dari dominasi logika kapital dalam dunia pendidikan.
Kampus, dalam banyak kasus, tidak lagi menjadi universitas dalam makna aslinya: tempat kebebasan berpikir. Ia lebih mirip korporasi akademik, dengan branding, komersialisasi jurnal, dan akuntabilitas semu dalam bentuk sertifikasi kompetensi. Mahasiswa diajarkan untuk berpikir sistematis, tetapi tidak kritis. Mereka mahir membuat PowerPoint, tapi gagap berdiskusi. Mereka hafal teori-teori, tapi asing terhadap realitas sosial sekitarnya.
Lebih tragis lagi, banyak dosen dan akademisi dikekang oleh logika publikasi. Mereka menulis bukan untuk mencerdaskan publik, melainkan untuk mengejar angka kum. Jurnal menjadi syarat administratif, bukan ruang dialog akademik. Pendidikan tinggi kehilangan roh epistemologisnya.
Reaktualisasi Konsep Mendidik: Dari Transfer Menuju Transformasi
Mendidik bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi membentuk watak, membuka cakrawala berpikir, serta memupuk kesadaran historis dan sosial. Dalam hal ini, kita harus kembali pada esensi pendidikan sebagai proses pembebasan, sebagaimana digaungkan tokoh-tokoh besar seperti Ki Hadjar Dewantara dan John Dewey.
Ki Hadjar menawarkan tiga asas dalam mendidik: ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Tiga asas ini menekankan peran pendidik sebagai teladan, fasilitator, dan pendorong. Ini bukan sekadar teori, tetapi falsafah praksis pendidikan yang memuliakan kemandirian murid. Sementara Dewey menekankan pentingnya pengalaman dan refleksi dalam proses belajar. Ia menganggap pendidikan sebagai proses sosial, bukan aktivitas terisolasi di ruang kelas.
Pendidikan mesti berpindah dari paradigma monolog menuju dialog. Dari pedagogi otoritatif menuju pedagogi partisipatoris. Di sinilah urgensi pendidikan kritis menjadi sangat relevan. Murid harus diajak berpikir, bukan dipaksa menghafal. Mereka harus dilibatkan dalam proses belajar sebagai subjek, bukan objek.
Guru Sebagai Intelektual Organik
Guru bukan hanya pelaksana kurikulum. Ia adalah agen transformasi sosial. Antonio Gramsci menyebut posisi ini sebagai intelektual organik — mereka yang tidak sekadar menyampaikan ilmu, tetapi menghidupkan kesadaran kritis dalam masyarakat. Guru yang ideal bukan yang menjejalkan materi, tetapi yang membangkitkan minat, membimbing pencarian makna, dan mendorong keberanian berpikir.
Namun, dalam realitas kontemporer, guru justru menjadi korban sistem. Mereka dibebani administrasi, dikejar penilaian kinerja, dan direndahkan secara ekonomi. Supremasi pendidikan tidak mungkin dicapai jika guru masih diposisikan sebagai pekerja rendahan. Negara harus menjadikan profesi guru sebagai pilar peradaban, bukan sekadar alat produksi nilai rapor.
Evaluasi, Instrumen Atau Jerat?
Salah satu tantangan terbesar dalam reaktualisasi pendidikan adalah sistem evaluasi yang reduktif. Ujian Nasional, tes standar, dan asesmen kognitif masif hanya mengukur satu dimensi dari kecerdasan manusia. Howard Gardner telah lama memperkenalkan konsep multiple intelligences, namun sistem pendidikan tetap terpaku pada logika angka dan kertas.
Evaluasi semestinya bersifat formatif, kontekstual, dan partisipatif. Ia bukan akhir dari proses belajar, melainkan bagian darinya. Evaluasi harus mendorong siswa untuk reflektif, bukan kompetitif. Dalam sistem yang baik, evaluasi menjadi alat pembelajaran, bukan sumber tekanan mental.
Digitalisasi Dan Distorsi Pendidikan
Era digital membawa potensi besar bagi transformasi pendidikan. Namun, jika tidak dikendalikan, ia justru mempercepat komodifikasi dan dekadensi nilai pendidikan. Platform daring, e-learning, dan AI berbasis edukasi memang mempermudah akses, tetapi juga membawa tantangan baru: dari plagiarisme akademik hingga pendidikan berbasis algoritma.
Alih-alih memperkuat nalar kritis, banyak media digital mempercepat konsumsi informasi dangkal. Pembelajaran menjadi sekadar kegiatan scrolling, bukan refleksi. Di sisi lain, ketimpangan digital (digital divide) menjadikan akses pendidikan berkualitas tetap menjadi hak istimewa bagi kelas sosial tertentu.
Digitalisasi harus dipahami bukan sebagai substitusi pendidikan tatap muka, melainkan sebagai pelengkap yang bersifat reflektif dan inklusif. Teknologi harus tunduk pada prinsip pedagogis, bukan sebaliknya.
Keluarga Dan Masyarakat Sebagai Ekosistem Pendidikan
Supremasi pendidikan tidak dapat dibebankan hanya pada sekolah atau pemerintah. Ia adalah tanggung jawab kolektif. Keluarga, lingkungan sosial, dan budaya komunitas turut membentuk kualitas pendidikan. Di sinilah pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang mendukung nilai-nilai kritis, empati, dan kolaborasi.
Sayangnya, keluarga sering kali terjebak dalam logika nilai. Anak yang berprestasi diukur dari nilai ujian, bukan etika atau kreativitas. Pendidikan informal dalam rumah — tentang rasa hormat, kepedulian sosial, dan kemampuan menyimak — sering kali luput karena digantikan oleh les dan bimbel.
Masyarakat pun perlu dikembalikan sebagai ruang belajar. Taman baca, diskusi publik, dan forum kebudayaan harus dihidupkan kembali. Karena pendidikan sejati tidak dibatasi oleh dinding sekolah.
Kebijakan Yang Progresif Dan Berbasis Etika
Supremasi pendidikan menuntut kebijakan publik yang tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga etis secara moral. Anggaran pendidikan harus disalurkan dengan adil, tepat guna, dan bebas dari korupsi. Selain itu, pendekatan kebijakan harus bersifat partisipatif, melibatkan pendidik, siswa, dan masyarakat dalam proses penyusunan dan evaluasi.
Pemerintah harus keluar dari pola pikir proyek dan mulai membangun visi pendidikan jangka panjang. Bukan sekadar mengejar sertifikasi internasional, tetapi membangun fondasi kultural dan intelektual bangsa. Negara yang besar bukan hanya dilihat dari infrastruktur fisiknya, tetapi dari kedalaman intelektual warga negaranya.
Pendidikan Sebagai Jalan Peradaban
Supremasi pendidikan adalah supremasi dalam mendidik. Ia bukan soal nilai, gelar, atau sertifikat, melainkan tentang kemampuan menciptakan manusia merdeka, beradab, dan berintegritas. Pendidikan sejati bukan yang mencetak juara lomba, melainkan yang membentuk pribadi utuh.
Jika kita ingin bangsa ini bermartabat, maka pendidikan harus dikembalikan pada jalurnya sebagai ruang pembebasan. Reaktualisasi paradigma mendidik bukan pilihan, tetapi keharusan sejarah.
Karena hanya dengan mendidik yang benar, kita membentuk bangsa yang berdaulat secara intelektual dan bermartabat secara etika. 
*) Khairul A. El Maliky, Pengarang Novel, Pemerhati Sosial Dan Budaya, Esais, Dan Cerpenis Yang Telah Menulis Banyak Tulisan Di Media Massa. Bukunya Yang Telah Terbit Berjudul: Akad, Kalam Kalam Cinta Dan Pintu Tauhid (2024), Sweet Girl Dan Cinta Tapi Beda (2025), Kitab Mengenal Diri Yang Sebenarnya Diri Dan Gus Dur Dan Tuhanpun Tertawa (Segera) Yang Diterbitkan Oleh MNC Publishing.
- Sikat Premanisme, Polres Banjarnegara Gelar Patroli Besar
- Operasi Aman Candi 2025: Penegak Hukum Dan Aparat Boyolali Bergerak Lindungi Kawasan
- Polres Boyolali + Kodim Boyolali + Satpol PP = Patroli Skala Besar Operasi Aman Candi 2025