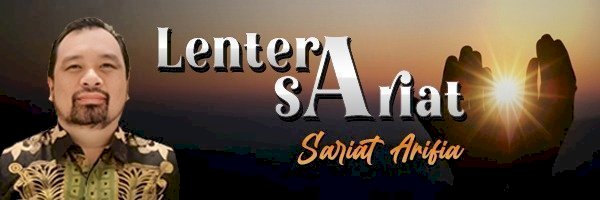- Malik Ibrahim, Bukan Sekedar Saudagar
- Dibalik Kejayaan Demak: Patih Unus dan Sunan Kudus Pendukung Setia Raden Trenggono
- Dari Kejayaan Hingga Konflik: Penyerbuan Demak Terhadap Portugis Di Malaka
Baca Juga
(Tulisan ini bagian dari Historiografi Sejarah islam dan hukum islam di Nusantara)
Perlunya Dekolonialisasi dan Dekonstruksi dalam Membaca Sejarah Jepara dan Kota di Pulau Muria dan sekitarnya
Penulisan sejarah Islamisasi dan hukum Islam di Jepara, sebagaimana wilayah pesisir Jawa lainnya, tidak dapat dilepaskan dari persoalan historiografis warisan kolonialisme.
Pendekatan dekolonisasi dan dekonstruksi menjadi penting untuk membongkar narasi-narasi mapan yang mungkin dibentuk oleh kepentingan atau cara pandang tertentu.
Dua jenis sumber utama yang sering dirujuk untuk periode ini, yakni catatan kolonial awal (seperti karya sejarawan Belanda H.J. de Graaf [sumber: 4834-4973]) dan sumber tradisional Jawa (seperti Babad Tanah Jawi), perlu dibaca secara kritis. Tidak mudah karena mendarah daging dan sudah di populerkan ratusan tahun , tapi hal ini wajib kita lakukan.
Karya De Graaf, meskipun penting karena didasarkan pada sumber Belanda dan Jawa, ditulis dalam kerangka ilmu sejarah Eropa era kolonial yang mungkin memiliki asumsi tertentu tentang peradaban Timur dan proses Islamisasi.
Di sisi lain, Babad Tanah Jawi, sebagaimana dianalisis oleh Prof Willem Remmelink, bukanlah catatan sejarah objektif melainkan lebih berfungsi sebagai sarana legitimasi kekuasaan dinasti Mataram, penuh dengan campuran mitos, legenda, dan fokus pada genealogi serta perebutan kekuasaan antar elite (" adu domba dan perang").
Remmelink menekankan pentingnya memahami proses penyalinan, penyuntingan, dan agenda politik di balik berbagai versi Babad, yang membuatnya problematis jika dijadikan rujukan primer tanpa kritik.
Narasi Babad seringkali mengabaikan aspek fundamental seperti peran perdagangan dalam penyebaran Islam, sebuah poin yang justru disaksikan dan dicatat oleh sumber sezaman seperti Tomé Pires.
Oleh karena itu, pandangan yang menekankan dekonstruksi terhadap sumber-sumber ini, seperti yang diusung oleh Leon Buskens dan Baudouin Dupret mengenai "penemuan" Hukum Islam oleh Barat, menjadi relevan.
Kita wajib dan harus mempertanyakan apakah narasi De Graaf dan Babad mengenai kebangkitan Demak dan peran Jepara di dalamnya merupakan bagian dari 'propaganda'—baik kolonial maupun legitimasi Jawa—yang perlu dibongkar untuk melihat realitas historis yang lebih kompleks, terutama yang berkaitan dengan peran masyarakat maritim pesisir itu sendiri.
Posisi Geografis Pulau Muria sebagai Satu Ekosistem Ekonomi, Maritim, Penyebaran Islam dan Pertahanan
Jangan sekali kali melihat sejarah kota kota di pesisir utara jawa, sebagai pecahan pecahan yang berdiri sendiri karena pandangan ini merupakan titipan kolonialisme.

Sumber: Internet
Untuk memahami sejarah Jepara dan wilayah sekitarnya (Tedunan/Kudus, Demak, Pati), penting untuk melihat posisi geografisnya yang unik pada periode abad ke-16. Wilayah yang kini menyatu dengan daratan Jawa ini, pada masa lalu merupakan Pulau Muria, yang terpisah dari daratan utama Jawa oleh selat sempit (Selat Muria).
Perspektif Tomé Pires dalam Suma Oriental secara implisit mendukung gagasan ini. Ketika Pires mendeskripsikan kerajaan-kerajaan di pesisir utara, ia memetakan Cirebon, Demak, Jepara, Rembang, hingga Tuban sebagai entitas pesisir yang berbeda dari kerajaan pagan di pedalaman yang ia sebut sebagai "Jawa" (dengan pusat di Daha/Majapahit yang dikuasai Guste Pate.
Pires menggambarkan kota-kota di sekitar Gunung Muria (Jepara, Tedunan], Demak dan Rembang sebagai satu kelompok wilayah yang saling terkait, seringkali melalui hubungan kekerabatan para Patenya (Pati Unus di Jepara, Pate Orob/Morob di Tedunan/Rembang), dan memiliki dinamika sendiri yang berbeda dari Demak (meskipun ada aliansi/ketundukan) maupun dari Tuban (yang bersekutu dengan Guste Pate).
Pires secara spesifik menyebut Jepara sebagai "kunci bagi seluruh Jawa, mengingat letaknya yang di tengah dan di puncak" di jalur pesisir utara.
Bagi saya, kalimat kunci ini bukan kalimat main main, mengandung kalimat yang sangat mendalam mengingat bahwa pada masa itu, pasar terbesar di asia Tenggara adalah Malaka.
Maka baik secara perdagangan, maupun secara kemaritiman dan pertahanan Pelabuhan Jepara sudah di perhitungkan oleh Portugis dengan matang matang untuk di sebut sebagai “Kunci” untuk pengusaan tanah Jawa, (belakangan Portugis datang memukul Jepara dari arah Selatan).
Maka Pemisahan geografis oleh Selat Muria pada masa itu secara logik menciptakan sebuah ekosistem sosial, ekonomi, dan politik yang lebih berorientasi pada dunia maritim dan perdagangan Selat Malaka daripada kerajaan agraris di pedalaman Jawa. Mereka lebih tepat dilihat sebagai satu kesatuan geopolitik pesisir yang terpisah dari 'pulau Jawa' utama pada masa Pires.
Kesatuan ekosistem ini terlihat jelas dalam beberapa aspek kunci:
- Ekosistem Maritim dan Perdagangan:
Posisi di pesisir Laut Jawa dan diapit Selat Muria menjadikan kawasan ini berorientasi kuat pada dunia maritim. Pelabuhan-pelabuhan seperti Jepara (disebut Pires pelabuhan terbaik dan "kunci bagi seluruh Jawa" di pesisir, Demak (pusat politik dengan akses laut, dan kemungkinan Juwana berfungsi sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan lokal, regional (ke Malaka, Pasai, Sumatra, Kalimantan, Maluku), hingga terhubung ke jaringan rempah global [Arif Akhyat, Mufrodi].
Pires mencatat kapal-kapal dari Jepara, Demak, dan sekitarnya membawa beras dan bahan makanan ke Malaka, sementara mereka mengimpor tekstil India (Gujarat, Keling), barang Tiongkok, dan komoditas lain. Selat Muria sendiri pada masa itu berfungsi sebagai jalur transportasi air internal yang efisien.
Kawasan ini, seperti dianalisis Arif Akhyat untuk Jepara, menjadi sebuah "kosmopolis" tempat bertemunya berbagai pedagang dan budaya, yang didukung oleh jalur maritim (William Dalrymple - The Golden Road How Ancient India Transformed the World (Bloomsbury) yang membawa para pendatang—yang menurut Pires dan De Graaf turut membentuk elite penguasa lokal.
- Ekosistem Penyebaran Islam:
Keterbukaan dan konektivitas maritim menjadikan kawasan Muria-Demak sebagai pusat persemaian dan penyebaran Islam awal yang terpadu di Jawa. Kita abaikan saja narasi narasi hubungan yang di bentuk pada masa kolonialisasi, tentang bagaimana hubungan antara wilayah Muria – Demak menjadi rusak karena cerita cerita yang tidak jelas.
Studi di lapangan tentang Nisan Nisan yang berada di Kawasan Kawasan ini cmenceritakan tentang masifnya penyebaran dan Kekuatan pedagang Islam pada masa itu di wilayah wilayah Muria-Demak.
Kehadiran para pedagang ini, tidak hanya sebagai penyebar agama tetapi juga sebagai figur otoritas keagamaan dan hukum awal, membentuk lanskap sosio-religius yang khas di kawasan ini. Interaksi antara ajaran Islam normatif (Mazhab Syafi'i, merujuk Coulson dengan praktik historis dan budaya lokal terjadi secara intensif dalam ekosistem pesisir yang dinamis ini.
- Ekosistem Pertahanan:
Kawasan ini juga berfungsi sebagai satu kesatuan kekuatan maritim dan pertahanan. Armada besar Demak-Jepara yang dipimpin Pati Unus untuk menyerang Malaka pada ~1512-1513, meskipun gagal, menunjukkan kapasitas militer maritim yang signifikan yang dapat dimobilisasi dari gabungan sumber daya wilayah ini.
Pires mencatat Jepara memiliki kapal, sementara Rembang adalah pusat pembuatan kapal. Kekuatan maritim Jepara yang berkelanjutan di bawah Ratu Kalinyamat pada pertengahan abad ke-16 [sumber: Pinto 5021-5022] semakin menegaskan potensi pertahanan kawasan Muria.
Posisi geografisnya yang terlindung Selat Muria di satu sisi dan Laut Jawa di sisi lain juga memberikan keuntungan defensif. Saya sendiri menilai bahwa hubungan antara Jepara, Demak, Kudus dan Pati, merupakan kombinasi kekuatan darat yang berpusat di Demak, maritim di Jepara dan dan Pati sebagai garda pertahanan di sebelah barat dalam Pulau Muria.
Kudus berada di Kawasan inti terdalam, sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Tengah pada masanya. Pernyataan Pires bahwa Jepara adalah "kunci bagi seluruh Jawa" dapat dimaknai tidak hanya secara ekonomi tetapi juga strategis-militer dalam konteks perebutan hegemoni di pesisir utara melawan sisa-sisa kekuatan darat Majapahit/Daha maupun potensi ancaman eksternal seperti Portugis.
Pendekatan historiografis yang memandang Jepara, Kudus, Pati, dan Demak sebagai wilayah-wilayah terpisah semata, hanya berdasarkan struktur administratif kadipaten di bawah Demak seperti yang sering digambarkan dalam narasi Babad (yang dikritisi Remmelink) atau perspektif kolonial, berisiko mengabaikan koherensi internal dan integrasi fungsional kawasan ini.
Realitasnya, hingga abad ke-16, wilayah Pesisir Muria-Demak lebih tepat dipahami sebagai satu ekosistem maritim, ekonomi, sosial-keagamaan (Islamisasi), dan pertahanan yang terpadu, yang dibentuk oleh kondisi geografis uniknya dan orientasi kuatnya pada dunia luar melalui jalur laut.
Pesisir Muria-Demak sebagai kota Kosmopolitan dalam Konsep Jaringan Perdagangan Dunia: Perspektif "Golden Road", "Silk Road", dan "Spice Route"
Memahami karakter unik Jepara dan kawasan pesisir di sekitarnya (termasuk Kudus, Pati, Demak) tidak cukup hanya dengan melihat dinamika internal Jawa, tetapi harus menempatkannya dalam konteks jaringan perdagangan global yang telah terbentuk selama berabad-abad.
Kawasan ini, yang secara geografis pada periode abad ke-15/16 masih dipengaruhi oleh keberadaan Selat Muria, bukanlah wilayah terisolasi, melainkan sebuah simpul penting yang secara konsisten terintegrasi ke dalam jalur-jalur perdagangan utama dunia, yang dikenal melalui berbagai konsep seperti "Golden Road", "Silk Road", dan "Spice Route".
Mengadopsi kerangka "Golden Road" dari William Dalrymple, kita melihat bagaimana Nusantara, termasuk pesisir utara Jawa, sejak milenium pertama Masehi telah menjadi bagian dari jaringan maritim yang menyebarkan peradaban India (Hindu-Buddha) melalui perdagangan dan migrasi.
Jalur laut kuno ini membentuk fondasi konektivitas dan keterbukaan budaya yang kemudian dimanfaatkan oleh gelombang pengaruh berikutnya, termasuk Islam.
Selanjutnya, penting untuk memahami konsep "Silk Road" tidak hanya sebagai jalur darat antara Tiongkok dan Mediterania, tetapi sebagai jaringan pertukaran Eurasia yang kompleks dan mencakup jalur maritim yang signifikan, sebagaimana ditekankan oleh Daniel Waugh.
Waugh mengkritik definisi sempit dan berpendapat bahwa rute laut melalui Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan—yang secara inheren melewati Nusantara—merupakan bagian integral dari pertukaran barang, ide, dan teknologi antar benua selama ribuan tahun. Dalam konteks ini, pelabuhan-pelabuhan di Pesisir Muria-Demak berfungsi sebagai titik transit dan distribusi penting dalam jaringan maritim global ini.
Pada periode Islamisasi dan kebangkitan kesultanan-kesultanan pesisir (abad ke-15/16), kawasan Muria-Demak memainkan peran sentral dalam "Spice Route" (Jalur Rempah).
Seperti diuraikan oleh Ali Mufrodi, jalur ini menghubungkan sumber rempah-rempah di Maluku dengan pasar di Asia Barat dan Eropa, melintasi pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Meskipun bukan penghasil utama rempah, Jepara, seperti dianalisis oleh Arif Akhyat, berfungsi sebagai "Kosmopolis Rempah"—sebuah hub pelabuhan vital yang memfasilitasi jaringan perdagangan dunia ini.
Tomé Pires memberikan bukti konkret mengenai peran ini pada awal abad ke-16. Ia mencatat kehadiran kapal dan pedagang dari berbagai penjuru dunia di pelabuhan seperti Jepara dan Gresik, serta jenis barang yang diperdagangkan—rempah dari timur (cengkih, pala), barang dari barat (tekstil Gujarat/Keling, opium), dan barang dari utara (porselen/sutra Tiongkok via perantara).
Integrasi ke dalam jalur perdagangan dunia ini secara langsung membentuk karakter budaya pesisir Jepara dan sekitarnya. Penekanan Pires dan De Graaf pada kemungkinan asal-usul asing bagi sebagian elite penguasa (misalnya kakek Pati Unus dari Laue/Kalimantan- Pulau Laut menurut saya], terlepas dari akurasi genealogisnya, menegaskan bahwa kawasan ini merupakan titik temu berbagai kelompok etnis dan budaya (Melayu, Jawa, Tionghoa, Arab, Persia, India/Gujarat/Keling, dll.).
Hal ini, sebagaimana argumen Arif Akhyat, menciptakan sebuah masyarakat dan budaya pesisir yang bersifat kosmopolitan dan hibrid, yang berbeda dari budaya pedalaman Jawa yang mungkin lebih agraris dan homogen.
Praktik keagamaan (Islamisasi) dan hukum yang berkembang di wilayah ini pun tak lepas dari pengaruh interaksi global yang difasilitasi oleh posisinya dalam jaringan Golden Road, Silk Road (maritim), dan Spice Route ini. (bersambung)
- Demo Hari Buruh di Semarang Rusuh, Ketua DPC SPSI Jepara: May Day Harusnya Kondusif
- Kasus Predator Seks Mencuat, Warga Tahunan: Lingkungan Kami Religius
- Pembelajaran Seni Ukir di Jepara, Gugah Minat Pelajar Perempuan dan Turis Asing